Janggut di Dagu: Ketika Politik Tak Lagi Mendengar
Pengambilan keputusan politik di negeri ini makin elitis. Dialog publik kian redup. Kebijakan datang bagai wahyu: satu arah, dari atas ke bawah. Ia bukan hasil dari musyawarah antara rakyat dan pemimpin, melainkan produk dari pertemuan-pertemuan sempit, terbatas, di ruang tertutup. Kadang, kita memang disuguhi pemimpin dengan kebijakan populis—pro rakyat, katanya. Namun, bila ditelusuri, populisme itu kerap lahir bukan dari proses partisipatif yang sehat, melainkan dari kalkulasi elektoral dan dorongan personal. Ini bukan demokrasi deliberatif, ini sekadar pertunjukan tunggal yang dibalut sorak-sorai.
Lihatlah misalnya fenomena Ahok dan Dedi Mulyadi. Keduanya tampil dengan gaya kepemimpinan yang kuat, penuh gestur simbolik terhadap rakyat kecil. Ada tindakan cepat, gaya blusukan, dan narasi keadilan sosial. Namun, apakah kebijakan mereka lahir dari dialog publik yang substansial? Apakah keputusan-keputusan mereka adalah hasil dari percakapan bersama dengan masyarakat terdampak, atau hanya dari intuisi pribadi yang dikemas apik?
Dalam demokrasi yang matang, partisipasi publik tidak berhenti pada pemilu dan survei elektabilitas. Demokrasi yang sehat mensyaratkan keterlibatan aktif warga dalam penyusunan kebijakan, bukan sekadar dalam menonton pelaksanaannya. Di sinilah relevan pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik (public sphere), di mana warga negara berdialog sebagai sesama, menyampaikan pendapat, memberi masukan, menyanggah, dan membentuk opini publik yang rasional. Kebijakan, dalam kerangka ini, idealnya adalah hasil dari deliberasi—musyawarah terbuka yang setara, bukan sekadar dekrit dari para pemegang kekuasaan.
Namun, kita sedang berjalan mundur. Ruang deliberatif itu makin menyempit. Forum-forum konsultasi publik hanya menjadi formalitas. Banyak kebijakan lahir tanpa proses dialog, bahkan sekadar mendengar pun tidak. Elite mengambil keputusan di bilik-bilik kecil, lalu mendorongnya ke publik melalui media dan buzzer.
Gejala ini paling tampak di tubuh partai politik. Kita tak lagi menyaksikan kompetisi terbuka dalam pemilihan pemimpin partai. Tak ada lagi momen demokratis seperti ketika Hamzah Haz berhadapan dengan AM Saefuddin, atau Akbar Tanjung berhadapan dengan Jusuf Kalla, atau ketika Sutrisno Bachir berhadapan dengan Fuad Bawazier. Sekarang, kongres dan muktamar hanya sekadar menstempel keputusan elite. Ketok palu menjadi simbol bahwa semua sudah beres, bahkan sebelum forum dibuka.
Rakyat, kader, dan bahkan kelas menengah tidak lagi punya daya tawar. Mereka menjadi seperti janggut yang bergantung ke dagu. Dagu adalah simbol elite, janggut adalah mereka yang berharap tak terlepas. Ia tidak menapak ke bumi seperti kaki yang kuat, hanya menggantung, mengikuti ke mana dagu bergerak.
Di sinilah letak krisisnya: kelas menengah kita, yang seharusnya menjadi penghubung antara elite dan rakyat, justru kehilangan independensinya. Mereka alih-alih menjadi penyambung nalar publik, malah berubah menjadi rent-seeker yang sibuk mencari cantolan ke kekuasaan. Mereka menjadi janggut, bukan tiang penyangga.
Amy Gutmann dan Dennis Thompson dalam Why Deliberative Democracy? menekankan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi dari proses yang mendahuluinya. Proses deliberatif—yakni dialog terbuka, inklusif, dan rasional—adalah syarat mutlak demokrasi yang adil. Bila partisipasi hanya menjadi kosmetik, maka yang tersisa adalah demokrasi semu, atau dalam istilah Colin Crouch: post-democracy. Sebuah keadaan di mana institusi demokrasi masih ada, tapi kendali substantif berada di tangan segelintir elite yang tak lagi mendengar publik.
Kehilangan peran kelas menengah politik menyebabkan jurang antara elite dan akar rumput makin lebar. Tak ada lagi kelas perantara yang mampu menerjemahkan bahasa kekuasaan ke dalam kosa kata rakyat. Tak ada yang menjembatani, yang memfasilitasi dialog dua arah. Yang terjadi justru dominasi satu arah: dari atas ke bawah.
Akibatnya, rakyat di akar rumput terjebak dalam isu-isu kecil yang tidak punya pengaruh besar terhadap arah kebijakan. Mereka dijejali debat receh tentang simbol, gaya berpakaian, atau sensasi media sosial. Ketika perhatian mereka terbelah pada isu yang tak substansial, elite leluasa merancang kebijakan yang tak terawasi.
Rakyat di bawah menjadi seperti ayam yang dipancing dengan segenggam beras. Mereka berebut, mematuk, bertengkar, bahkan saling melukai hanya demi butir-butir kecil. Sementara para elite pesta besar di belakang, menikmati gulai tunjang dan beras dalam satuan ton. Ketika butiran beras itu habis, dilemparlah segenggam baru. Siklus ini berulang. Ayam tetap sibuk mematuk, lupa bahwa yang sebenarnya enak bukan butiran itu, tapi gulai tunjang yang disembunyikan.
Kita hidup dalam demokrasi prosedural, tetapi kehilangan demokrasi substantif. Institusi pemilu, partai, dan parlemen masih berdiri, tetapi esensi dialog dan partisipasi telah digerogoti. Jika kelas menengah tak kembali merebut perannya sebagai jembatan rasional antara elite dan rakyat, maka kita akan terus menjadi janggut—yang hanya berharap tidak lepas dari dagu, tanpa pernah mampu berdiri sendiri.


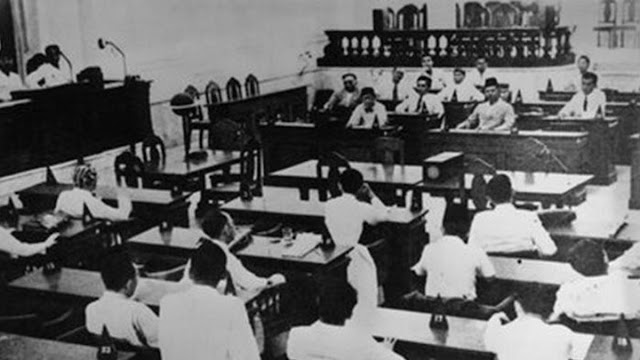
Komentar
Posting Komentar