Membaca Manuver Politik Felix lewat Teori Politik Asosiasi
Di tulisan sebelumnya, kita sudah mendapatkan identitas Felix Siauw, yakni Felix bukan sekadar ustadz atau penceramah agama di mimbar saja, melainkan Felix adalah juga politikus dari "Partai Pembebasan / Hizbut Tahrir" yang didirikan di Palestina pada tahun 1953. Dengan identitas sebagai politikus itu, kita dapat membaca sikap-sikapnya, termasuk dalam merespons konflik Israel-Iran. Sikap politik Felix tentu tidak lepas dari kalkulasi dan afiliasi ideologis partai politik Hizbut Tahrir tempat ia bernaung.
Baca : Memahami Felix Siauw sebagai Politikus Partai
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membaca manuver politik semacam itu secara lebih baik? Apa yang membuat seorang politikus seperti Felix, yang mempunyai identitas Muslim dan sangat mendukung kemerdekaan Palestina serta membenci Israel, namun memilih untuk menyebarkan propaganda negatif tentang Iran? Lebih lanjut, jika ia membenci Syiah dan Israel dalam waktu bersamaan, mengapa ia memilih menyerang Iran lebih keras ketika Islam membutuhkan soliditas dalam menghadapi Israel? Bukankah ini semacam paradoks?
Untuk memahami manuver semacam ini, kita perlu keluar dari kacamata moral dan masuk ke cara kerja dunia politik, yakni tentang bagaimana seorang aktor memilih siapa yang harus diserang atau dibela, bukan berdasarkan benar-salah, melainkan kepentingan ideologis. Di sinilah pendekatan perilaku politik asosiasi menjadi penting. Dalam pendekatan ini, pilihan sikap seseorang dalam berasosiasi bukan dipengaruhi oleh kebenaran objektif. Ia lebih dipengaruhi oleh kalkulasi tentang siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang paling mengancam eksistensi ideologisnya. Salah satu teori klasik dalam pendekatan ini dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dalam bukunya Politics: Who Gets What, When, How (1936). Lasswell menyebutkan bahwa tindakan politik sangat dipengaruhi oleh persepsi ancaman dan peluang terhadap distribusi nilai-nilai yang dianggap penting. Dengan kata lain, siapa yang paling mengancam “dunia ideal” versi seorang politikus, maka dialah yang akan jadi sasaran utama kritiknya. Persepsi tentang siapa yang mengancam dunia ideal itu tidak lahir dari ancaman objektif, melainkan dari siapa yang paling merusak “cita-cita” ideologisnya.
Dalam kasus Felix, dunia ideal yang ia impikan adalah sistem khilafah seperti yang dirumuskan oleh Hizbut Tahrir. Sebuah negara mondial yang diasumsikan sebagai kelanjutan eksistensial entitas khilafah yang dibangun dalam Saqifah Bani Sa'idah di jam-jam pertama kemangkatan Rasulullah. Khilafah HT adalah suksesor dari entitas yang berkesinambungan sejak masa Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah (termasuk shadow caliphate di Kairo), hingga Utsmaniyah di Istanbul. Entitas inilah yang menurut Hizbut Tahrir terjeda sejak 1924 dan belum dapat dibangkitkan.
Tentunya, sistem ini sangat bertolak belakang dengan Wilayatul Faqih-nya Iran. Wilayatul Faqih tidak diandaikan sebagai suksesor empat fase ala HT tersebut (Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah), melainkan sebuah struktur yang berangkat dari entitas yang sama sekali berbeda dengan argumentasi eksistensial yang berbeda pula. Wilayatul Faqih tidak menjadikan empat fase itu sebagai precursornya. Bagi Wilayatul Faqih, sistemnya adalah produk dari fase yang berbeda yakni Nubuwwah, Imamah, Mahdawiyah, dan Ghaibah. Perbedaan dalam melihat fase-fase ini menghasilkan perbedaan dalam membaca sejarah, menarik ajaran, hingga merumuskan ke mana ujung sebuah sistem akan diarahkan.
Baca : Rahbar: Pemimpin Tertinggi Iran yang Lebih Kuat dari Presiden
Oleh karena itu, meskipun Felix juga sepertinya anti-Israel dan Iran saat ini menjadi satu-satunya negara yang secara terbuka melawan Israel secara militer, posisi itu tidak lantas membuat Felix bersimpati. Justru karena Iran berhasil menampilkan model pemerintahan Islam yang berhasil terwujud tapi dalam versi yang “salah” menurut cita-cita ideologis HT, kehadiran Iran oleh Felix dianggap menjadi ancaman eksistensial terhadap visi politik partai HT.
Dalam dunia politik, hal semacam ini disebut “asosiatif selektif”. Teori ini dikembangkan oleh Giovanni Sartori dalam bukunya Parties and Party Systems (1976). Ia menyebut bahwa asosiasi politik tidak selalu mengikuti garis ideologis linier, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan identitas dan diferensiasi. Jika dua kubu memiliki musuh bersama tapi satu sama lain saling mengancam secara simbolik, maka aliansi tak mungkin terjadi. Bahkan, mereka justru akan lebih keras menyerang satu sama lain demi menjaga diferensiasi identitas.
Itulah yang sedang kita lihat. Felix lebih memilih membangun narasi bahwa “Iran dan Israel itu bestie” ketimbang berasosiasi dengan Iran dalam memukul musuh bersamanya. Ia tidak mau mengakui bahwa musuhnya (Israel) sedang dilawan oleh pihak lain (Iran) karena tidak sejalan secara ideologis. Ia malah memilih untuk menjalankan strategi klasik politisi, yaitu diferensiasi dan delegitimasi. Ia lebih memerlukan diferensiasi antara identitasnya dengan identitas Iran ketimbang mendukung Iran dalam melawan Israel. Malahan, ia mendelegitimasi tindakan Iran untuk semakin membedakan dirinya.
Lebih jauh, fenomena ini juga bisa dibaca dengan kerangka symbolic politics theory seperti dikembangkan oleh Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics (1964). Edelman menjelaskan bahwa tindakan politik sering kali tidak bertujuan menghasilkan solusi konkret, melainkan membentuk persepsi publik demi mempertahankan dukungan. Dalam logika ini, serangan Felix terhadap Iran bukan karena Iran salah langkah, tapi karena narasi tentang “Iran dan Israel itu bestie” diperlukan untuk menjaga posisi HT sebagai satu-satunya penyelamat dunia Islam versi mereka. Untuk mempertahankan posisi itu, HT memerlukan musuh simbolik. Dan sejak keberadaan Israel sudah jadi musuh bersama semua orang, musuh simbolik itu harus dicari dari dalam umat sendiri, dari yang identitasnya paling “mirip” (sesama Islam, sesama memusuhi Israel), tapi harus dilegitimasi sebagai sumber bahaya secara ideologis. Maka muncul tiga definisi untuk delegitimasi itu, yakni Iran yang Syiah, Iran yang bestie dengan Israel, dan Iran yang revolusinya lebih membahayakan cita-cita ideal HT.
Maka dari itu, kita perlu membaca Felix sebagai politisi, bukan sebagai ustadz semata. Jika kita membaca posisinya sebagai ustadz, kita akan menganggap ucapannya sebagai kebenaran ilmiah atau ajaran agama. Padahal, seperti halnya politisi lain, ucapannya adalah bagian dari strategi. Baik strategi diferensiasi, strategi delegitimasi, maupun strategi dalam mempertahankan dukungan menuju visi politiknya. Ucapan Felix tentang “Iran dan Israel itu bestie” bukanlah data sejarah yang jujur, melainkan sebuah manuver ideologis. Ia sedang berpolitik.
Maka pertanyaannya bukan lagi “mengapa Felix bicara begitu?”, tapi “untuk siapa Felix bicara?”. Dan ketika jawabannya adalah untuk cita-cita ideologis partainya, bukan untuk Palestina, kita jadi tahu harus bersikap seperti apa. Dengan kesadaran kita bahwa yang sedang berbicara adalah politisi, kita sadar pula bahwa semua pernyataannya harus dibaca sebagai bagian dari strategi politik. Termasuk ketika ia mengenakan peci, memegang mikrofon di masjid, dan mengutip ayat suci.
Di mimbar apa pun, politikus tetaplah harus kita baca sebagai politikus.
Sumber gambar : Jaihoon.com


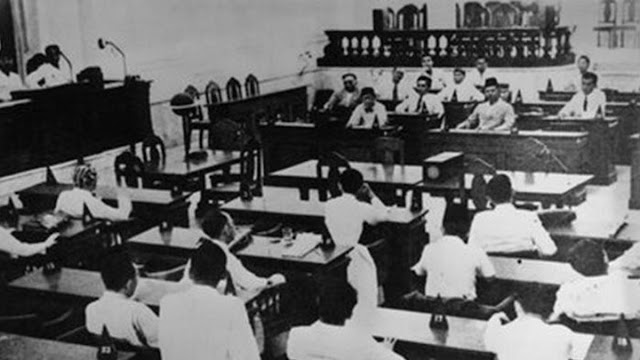
Komentar
Posting Komentar