Pelajaran tentang Sirkulasi Elit dari Rekonsolidasi Aristokrat Quraisy
Fenomena rekonsolidasi kekuasaan lama bukan hanya terjadi di zaman modern. Dalam sejarah Islam awal, pola ini terlihat jelas pasca-Fathul Makkah. Aristokrat Quraisy yang dipimpin oleh Bani Umayyah sempat dikalahkan secara militer dan politik oleh gerakan revolusioner Muhammad. Namun, hanya dalam waktu sekitar lima belas tahun setelahnya mereka mampu memulihkan kekuatan dengan cara yang lebih canggih dan adaptif.
Dari Kekalahan Menuju Restorasi
Fathul Makkah meruntuhkan struktur kekuasaan lama Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Meski demikian, kelompok aristokrat ini tidak benar-benar hilang. Mereka mempertahankan modal sosial, jaringan keluarga, dan kemampuan diplomasi. Faktor-faktor ini membuat Muhammad tidak sepenuhnya dapat menghapus peran mereka. Pengaruh mereka tetap diakui meski relatif terkontrol. Dalam Perang Hunain, misalnya, Muhammad memberikan bagian rampasan yang besar kepada mereka sehingga memicu protes dari para aktor revolusioner di sekelilingnya.
Setelah Muhammad wafat, Bani Umayyah perlahan kembali ke pusat kekuasaan dan mencapai puncaknya saat Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pada tahun 23 Hijriah. Masa kekuasaan Utsman ditandai dengan kembalinya jaringan kekuasaan dan kekerabatan Bani Umayyah ke dalam struktur politik yang awalnya justru dibangun oleh lingkaran revolusioner Muhammad.
Ali sebagai Gangguan Eksistensial
Restorasi ini terguncang ketika Ali bin Abi Thalib, kerabat dekat Muhammad, naik sebagai khalifah. Di mata aristokrat Quraisy, Ali bukan sekadar lawan politik biasa, tetapi ancaman eksistensial yang bisa meruntuhkan fondasi kekuasaan yang baru mereka bangun. Ali berupaya mengembalikan pemerintahan pada nilai-nilai awal Islam yang lebih meritokratis. Ia memecat para pejabat yang terkait pada jaringan Bani Umayyah, dan menempatkan kesetiaan pada prinsip Islam di atas kesetiaan kepada darah Quraisy. Langkah ini memutus jalur ekonomi dan kekuasaan yang menopang aristokrasi lama.
Tidak heran jika jaringan yang sudah terkonsolidasi itu melawan dengan sengit. Masa Ali hingga anaknya, Hasan dan Husain, menjadi periode paling berdarah dalam sejarah politik Islam awal. Konflik ini tidak semata-mata tentang tafsir agama, melainkan tentang hidup dan matinya dominasi elite lama. Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kini menjadi tokoh kunci Bani Umayyah, memainkan peran sentral dalam mengamankan kembali hegemoni mereka. Setelah menyingkirkan Ali dan Hasan, ia memperkokoh kekuasaan dengan menunjuk putranya, Yazid, sebagai penerus. Langkah ini bukan hanya konsolidasi politik aristokrasi lama, tetapi juga upaya memastikan bahwa tidak akan lagi ada pintu masuk bagi gerakan revolusioner Muhammad. Husain, cucu laki-laki Muhammad yang tersisa, menjawab langkah ini dengan perlawanan hidup-mati yang berujung pada tragedi Karbala.
Teori Konsolidasi Elit
Kemenangan Bani Umayyah ini bukan kebetulan atau sekadar hasil momentum politik sesaat. Polanya dapat dibaca melalui kacamata ilmuwan politik modern. Gaetano Mosca dalam The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica, 1896) menjelaskan bahwa elite politik mempertahankan kekuasaan dengan membangun jaringan dan mengendalikan distribusi sumber daya. Pandangan ini sejalan dengan teori Vilfredo Pareto dalam The Mind and Society (Trattato di Sociologia Generale, 1916) yang menggambarkan konsep “peredaran elite” atau circulation of elites, yakni proses di mana elite lama dapat kembali berkuasa dengan menyesuaikan strategi terhadap perubahan zaman dan keadaan. Dalam kasus ini, Bani Umayyah menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa untuk bangkit dari kekalahan total di Fathul Makkah hingga kembali mendominasi hanya dalam tempo yang relatif singkat.
Bani Umayyah tidak hanya mempertahankan kekuasaan dengan senjata dan diplomasi, tetapi juga dengan membentuk “rezim pengetahuan” yang memastikan posisi mereka tetap terjaga di mata generasi berikutnya. Melalui kendali khutbah Jumat, penugasan para ulama istana, serta pembentukan narasi resmi yang menonjolkan stabilitas pemerintahan mereka, memori kolektif umat diarahkan untuk melihat mereka sebagai penguasa sah. Strategi ini membuat kekuasaan mereka tidak hanya bertahan secara politik, tetapi juga mengakar dalam ingatan sejarah masyarakat.
Dari Karbala ke Pemberontakan Zaid bin Ali
Kekalahan di Karbala tidak mengakhiri benturan tersebut. Beberapa dekade kemudian, riak perlawanan masih muncul. Zaid bin Ali, cucu Husain, memimpin pemberontakan di Kufah pada tahun 122 Hijriah. Ia mengusung semangat perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan, menjadi simbol bahwa perlawanan keluarga Muhammad terhadap aristokrasi lama tetap hidup meski peluang kemenangan kian kecil. Pemberontakan itu berakhir tragis, tubuh Zaid dikoyak dan disalib di alun-alun. Namun kematiannya tidak memadamkan sepenuhnya api perlawanan terhadap dominasi elite Quraisy. Bagi semangat revolusioner Muhammad, rekonsolidasi elite lama ini tidak akan pernah diterima begitu saja, bahkan jika nyawa menjadi taruhannya.
Sejarah ini menunjukkan bahwa sirkulasi elit jarang benar-benar memutus masa lalu. Lebih sering, ia justru menghidupkan kembali kekuatan lama dalam wujud baru, disertai strategi adaptasi yang tidak hanya mengamankan kekuasaan politik, tetapi juga membangun rezim pengetahuan yang menjaga citra mereka di mata generasi berikutnya. Dengan cara ini, potensi survivalitas mereka dalam lintasan sejarah meningkat berlipat.
Pelajaran untuk Kita: Mengapa Elite Lama Mudah Bangkit dan Bagaimana Menghadapinya
Fenomena kebangkitan elite lama yang sempat ditumbangkan bukan hanya soal kekuatan politik secara kasat mata, tetapi juga hasil strategi jangka panjang yang memadukan kekuasaan simbolik, jaringan sosial, dan kapasitas birokrasi yang matang. Antonio Gramsci mengingatkan kita bahwa kekuasaan tidak hanya didirikan lewat dominasi fisik, tetapi terutama lewat hegemoni budaya, kontrol atas narasi, ideologi, dan simbol yang membuat masyarakat menerima elite lama sebagai bagian “normal” dari kehidupan politik.
Jaringan sosial yang kuat dan patronase yang sudah lama dibangun oleh elite lama merupakan modal utama dalam rekonsolidasi kekuasaan. Mereka tidak hanya mengandalkan alat negara, tetapi juga jejaring keluarga, bisnis, dan kelompok sosial yang menjadi basis dukungan mereka. Melalui jaringan ini, elite lama dapat menyebarkan pengaruh secara luas dan menjaga solidaritas internal.
Selain itu, teori Political Opportunity Structure (POS) menjelaskan bahwa elite lama bisa bangkit kembali saat terjadi perubahan struktur politik yang membuka peluang bagi mereka. Misalnya, ketidakstabilan rezim baru, krisis ekonomi, atau pergeseran preferensi publik bisa menjadi momentum yang dimanfaatkan elite lama untuk mendapatkan legitimasi dan pengaruh kembali.
Elite lama biasanya memiliki keunggulan dalam kapasitas negara (state capacity) dan ingatan kelembagaan (institutional memory) yang belum sepenuhnya dikuasai rezim baru. Contohnya, Bani Umayyah sudah berpengalaman mengelola birokrasi sejak era perniagaan pra-Islam dan terus mengembangkannya selama masa kekuasaan, terutama di bawah Khalifah Utsman dan Gubernur Muawiyah di Syam. Mereka berhasil menyusun birokrasi yang lebih terstruktur dan efektif dibandingkan sistem yang dibangun oleh Muhammad, Ali, dan pendukungnya. Keunggulan ini membuat publik kala itu melihat rekonsolidasi Bani Umayyah sebagai solusi pemerintahan yang lebih stabil dan efisien. Sementara itu, rezim baru yang lahir dari perubahan cepat sering kekurangan pengalaman dan kapasitas birokrasi, sehingga kerap mengecewakan publik dan membuka peluang bagi elite lama untuk kembali mendapat dukungan sebagai pilihan yang lebih baik.
Fenomena kebangkitan elite lama ini dapat kita lihat dalam berbagai konteks kontemporer, seperti kembalinya sisa rezim Orde Baru di Indonesia, kebangkitan jaringan lama pasca kejatuhan rezim Moorsi di Mesir, atau kembalinya Thaksin di Thailand dan Marcos Jr di Filipina. Dalam semua kasus ini, elite lama mampu memanfaatkan kekuatan simbolik, peluang politik, jaringan sosial, serta kapasitas negara yang mereka miliki untuk merebut kembali posisi dominan.
Untuk menghindari hal ini, reformasi politik dan sosial seharusnya tidak sekedar mengganti elite secara formal, tetapi juga membangun kapasitas negara yang inklusif, memperkuat institusi demokrasi, dan menyusun narasi kolektif baru yang menolak hegemoni lama. Pendidikan politik dan penguatan civil society juga menjadi kunci dalam menolak dominasi kembali elite lama yang bermuatan kepentingan sempit dan sering merugikan publik.
Sumber gambar : artstation.com


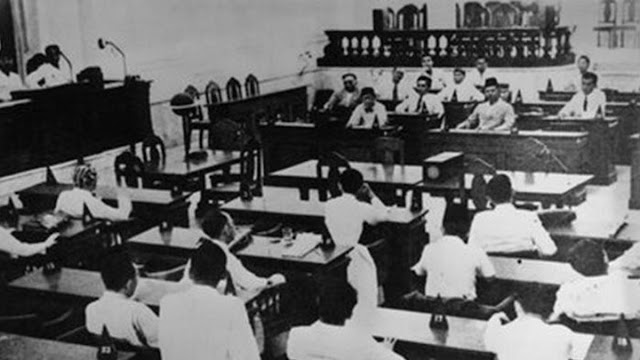
Komentar
Posting Komentar