Merindukan Masjid Tanpa Tabir
Saya merasa miris membaca kabar tentang pembakaran lemari penyimpanan peralatan shalat perempuan di tiga masjid di Maros, Sulawesi Selatan. Mirisnya karena pelaku telah berulang kali melakukannya dengan alasan bahwa perempuan tidak boleh beribadah di dalam masjid. Pandangan ini menurut saya cukup laten di kalangan umat Islam saat ini, meskipun dengan kadar manifestasi yang berbeda-beda. Ada yang termanifestasi melalui cara ekstrem seperti di Maros ini, ada juga dengan cara yang lebih halus di tempat lain. Namun akarnya sama berupa pandangan misoginis bahwa perempuan dan tempat ibadah tidak diperkenankan terlalu dekat.
Pengalaman di Maros ini amat berbeda dengan apa yang saya jalani ketika masih tumbuh di kampung dulu, khususnya di Payakumbuh. Saya menyaksikan nenek saya nyaris selalu shalat berjamaah lima waktu di masjid atau surau. Di tiap masjid itu shaf jamaah perempuan selalu lebih ramai daripada shaf jamaah laki-laki. Pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan tidak tinggi, hanya selutut sebagai penanda. Kita masih bisa saling berinteraksi. Malah di sebagian tempat, tak ada batas nyata, hanya ada satu shaf kosong antara lelaki dan perempuan supaya ada jarak. Namun apabila jamaah terlalu ramai, misalnya di bulan Ramadhan, shaf kosong itu kembali terisi sehingga tidak ada jarak antara jamaah lelaki dan perempuan kecuali jarak hati saja. Maksudnya, si lelaki jangan sampai mengintip ke belakang menyaksikan fisik ibu-ibu.
Saya masih ingat, kalau sedang berceramah—dahulu saya sering mengisi ceramah menggantikan orang tua, dan belakangan memiliki jadwal sendiri—saya masih bisa menyapa ibu-ibu dengan jelas. Pun jamaah lelaki dan perempuan masih bisa saling menyahut jika ada pertanyaan. Bahkan bisa saling berdiskusi ketika membahas rencana-rencana masjid.
Ketika merantau ke Jakarta, saya menyaksikan hal yang berbeda. Shaf perempuan sangat terbatas, kalaupun ada posisinya sulit dijangkau atau tidak nyaman ditempati. Misalnya di balkon lantai dua, di teras, atau di sudut sempit dengan tabir tinggi yang mengurung. Jamaah dan penceramah lelaki tidak bisa melihat jamaah perempuan, begitu juga sebaliknya. Keduanya seperti berada pada masjid yang berbeda sehingga diperlukan monitor TV untuk merelay ceramah ustadz ke ruang tertutup perempuan.
Saya tidak tahu hukum fiqihnya. Namun yang saya bayangkan, betapa terkurung rasanya jadi perempuan di balik tabir tinggi itu. Mereka tak dapat merasakan suasana masjid secara utuh seperti yang dirasakan jamaah lelaki. Dari kerangka ini saya bisa membayangkan mengapa kadang istri saya tidak begitu antusias menghadiri pengajian. Sebab sementara saya berada di lokus yang nyaman, bisa berinteraksi langsung dengan penceramah meski hanya lewat tatapan mata atau bahasa tubuh, istri saya berada dalam ruang tertutup tabir, hanya bisa melihat penceramah dari layar monitor. Jika begitu keadaannya, apa bedanya bagi istri saya antara datang langsung ke pengajian dengan menonton siaran pengajian dari YouTube? Sama-sama menatap monitor. Bedanya hanya lokasi menonton, dari menonton di rumah menjadi menonton masjid.
Suatu kali, di sebuah masjid saya pernah mempersilakan ibu-ibu yang tengah menyusun shaf di teras luar untuk masuk ke dalam. Di teras itu panas, sedangkan di dalam masjid ada AC. Lagi pula masjidnya belum penuh. Dua atau tiga shaf belakang masih bisa dimanfaatkan jamaah perempuan. Awalnya mereka ragu untuk masuk, seolah kehadiran mereka akan merusak kesucian masjid. Tetapi setelah saya kembali keluar dan menyuruh masuk, akhirnya mereka mau masuk. Saya tidak tahu bagaimana respons DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), apakah setuju atau tidak dengan ulah saya itu. Saya kan bukan DKM, hanya lelaki yang lagi nekat saja.
Saya merindukan masjid seperti yang dulu saya alami di kampung, ketika pembatas laki-laki dan perempuan cukup berupa penanda kecil saja, bukan penghalang pandangan apalagi pengurung jamaah perempuan.


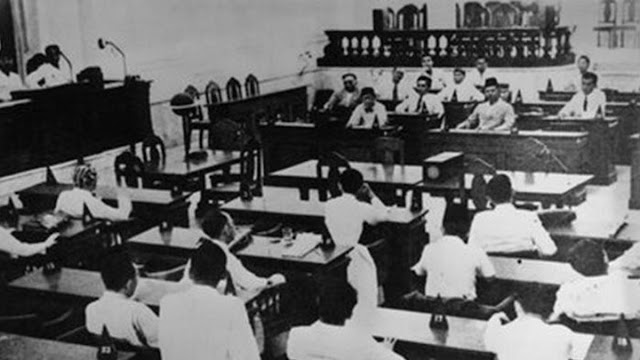
Semoga menginspirasi para DKM
BalasHapusAmiin, Thank you Bang @Said Amin
Hapus