Bukan Soal Keahlian, Tapi Periuk Kita Yang Terlalu Kecil
 |
Di tengah maraknya pelatihan vokasi, program sertifikasi daring, dan pendidikan tinggi massal, narasi umum yang berkembang di Indonesia terkait pengangguran adalah soal rendahnya keterampilan tenaga kerja. Pemerintah, lembaga swasta, hingga platform teknologi ramai-ramai berlomba mencetak talenta siap kerja, seolah-olah masalah utama ketenagakerjaan adalah kurangnya kompetensi individu.
Namun, jika kita melihat lebih jernih, akar persoalan justru lebih mendalam dan bersifat struktural. Masalah kita bukan semata pada keahlian, melainkan pada ukuran ekonomi yang terlalu kecil untuk menampung jumlah penduduk yang besar. Bahkan jika seluruh penduduk diberi pendidikan tinggi dan sertifikasi kelas dunia, tetap akan ada yang menganggur—karena tak ada cukup ruang dalam struktur ekonomi untuk menyerap mereka.
Analogi sederhananya begini, bayangkan sebuah periuk kecil yang harus membagi nasi kepada sepuluh orang. Masing-masing sudah dibekali piring dan sendok besar, bahkan diajarkan etiket makan. Namun jika isi periuknya tidak bertambah, tetap akan ada yang tak kebagian. Dalam konteks ini, periuk adalah kapasitas produksi nasional, terutama di sektor riil yang padat karya dan produktif—yakni industri manufaktur.
Sayangnya, Indonesia justru mengalami apa yang bisa disebut sebagai lompatan prematur ke era digital, tanpa terlebih dahulu memperkokoh sektor industrinya. Banyak negara maju menjadi kuat karena menyelesaikan fase industrialisasi secara tuntas, lalu melanjutkan ke sektor jasa dan digital. Indonesia justru melewatkan fase itu. Kita tergesa-gesa terjun ke ekonomi digital sebelum membangun fondasi produksinya.
Fenomena ini mengingatkan pada apa yang disebut para ekonom sebagai bubble economy—yakni ketika sebuah sektor tumbuh secara mencolok, tapi tanpa basis produksi riil yang kuat. Banyak talenta muda berbondong-bondong mengejar karier digital, membangun kanal YouTube, berjualan daring, hingga berburu adsense, padahal sumber nilai sektor ini sangat terbatas. Jika pendapatan iklan dan monetisasi digital masih bergantung pada industri yang lemah, maka ledakan minat ini tak ubahnya balon yang menggembung oleh harapan, bukan oleh produktivitas. Dan seperti semua balon, ia rawan pecah kapan saja.
Kita menyaksikan ledakan minat generasi muda terhadap profesi-profesi digital: menjadi konten kreator, YouTuber, pengembang aplikasi, atau penyedia jasa daring. Namun, ekonomi digital yang mereka masuki sebagian besar bersifat parasitik terhadap industri. Pendapatan dari adsense, afiliasi, atau monetisasi daring bersumber dari anggaran promosi sektor manufaktur dan perdagangan, bukan dari penciptaan nilai langsung.
Artinya, ekonomi digital saat ini tidak memperbesar periuk, melainkan hanya memperluas cara membagi nasi yang sedikit itu. Akibatnya, yang terjadi bukan pertumbuhan riil, tetapi rebutan asap dari periuk kecil. Bila ada yang berhasil mengambil banyak, pasti ada yang tak kebagian sama sekali.
Situasi ini berlawanan dengan two-sector model dari ekonom peraih Nobel, W. Arthur Lewis, yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi terjadi ketika tenaga kerja surplus dari sektor tradisional terserap ke dalam sektor modern seperti manufaktur. Tanpa sektor modern yang kokoh, surplus tenaga kerja akan terjebak dalam sektor informal yang tidak produktif—atau hari ini: sektor digital yang semu.
Lebih lanjut, Friedrich List, seorang ekonom Jerman abad ke-19, mengkritik negara yang membuka diri terhadap perdagangan bebas tanpa membangun industri nasional. Baginya, kekuatan ekonomi tak cukup dibentuk oleh pasar, tetapi harus melalui perencanaan industri yang matang. Negara yang menjual jasa digital tanpa membangun pabrik ibarat menjual bunga tanpa pernah menanam pohon. Ada tampilan estetik, tapi nihil fondasi produktif.
Masalah ini juga tercermin dalam dependency theory dari Raul Prebisch dan Andre Gunder Frank, yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang cenderung terjebak sebagai pemasok bahan mentah dan konsumen produk industri dari negara maju. Tanpa industrialisasi, kita akan terus berada di bawah dominasi nilai tambah negara lain—termasuk dalam ekosistem digital yang perangkat kerasnya kita impor, dan platformnya dikuasai raksasa global.
Solusi atas kondisi ini bukan sekadar lebih banyak pelatihan atau penyuluhan digital. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural ekonomi. Seperti dikatakan oleh ekonom kontemporer Dani Rodrik, transformasi ke sektor bernilai tambah tinggi tidak akan terjadi secara otomatis, tetapi membutuhkan intervensi aktif dari negara melalui kebijakan industri: mulai dari insentif fiskal, perlindungan cerdas, hingga pembangunan kawasan industri yang terintegrasi.
Tanpa kebijakan semacam itu, kita akan menyaksikan generasi muda yang terdidik tapi terpinggirkan. Mereka memiliki ijazah, keterampilan digital, bahkan jaringan global, tapi tidak menemukan ruang untuk berkontribusi karena fondasi produksi tidak tersedia.
Sebelum kita mengajak semua orang belajar coding, editing, atau menjadi influencer, mari kita tanya dulu satu hal penting: apakah sudah tersedia cukup pabrik, mesin, logistik, dan sistem produksi nasional yang butuh dikendalikan oleh teknologi itu? Jika belum, kita ibarat mengajarkan menyetir mobil—tanpa pernah membangun mobilnya.
Pembangunan ekonomi tidak dimulai dari layar, tetapi dari mesin. Bukan dari follower, tapi dari fondasi industri. Jika periuknya tetap kecil, secanggih apa pun alat makan kita, tetap akan ada yang kelaparan.

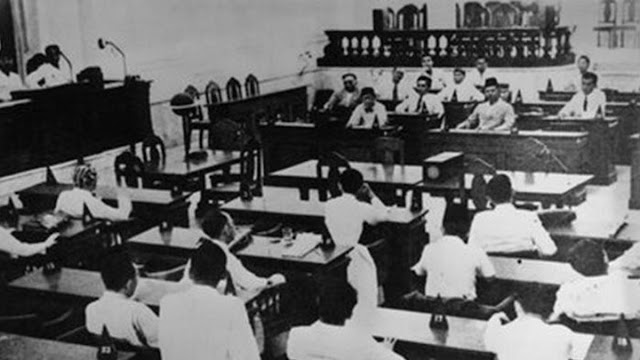
Komentar
Posting Komentar